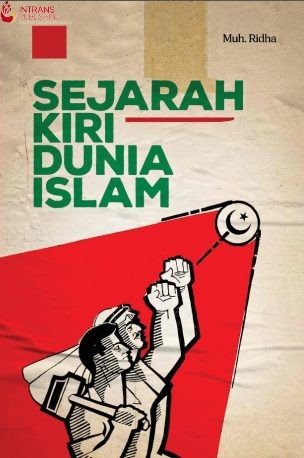
Buku Sejarah Kiri Dunia Islam merupakan kompilasi refleksi Muhammad Ridha atas kegelisahannya terhadap potret sejarah arus utama dan peminggiran sistematis terhadap persenyawaan antara pemikiran dan gerakan Islam dengan tradisi kiri—Marxisme, Sosialisme, dan Komunisme—khususnya dalam konteks Indonesia, meskipun cakupannya tidak terbatas pada wilayah ini.
Sejak tahun 1965, bukan hanya tradisi Kiri yang dibungkam; segala bentuk pemikiran, perkumpulan, dan pergerakan yang dianggap menantang, mempertanyakan, atau mengritisi rezim Orde Baru ikut dibungkam—termasuk Islam sebagai kekuatan politik alternatif. Namun, pada dekade 1980-an, kekuatan Islam mulai dirangkul: istilah Islam moderat muncul sebagai upaya memediasi ketegangan antara umat, pasar, dan negara. Sementara itu, label seperti Islam radikal atau fundamentalisme disematkan secara peyoratif dengan imaji ancaman ‘ekstremis’ terhadap modernitas untuk memudahkan proyek pelunakan dan kooptasi rezim bersama kapitalisme global. Di sisi lain, kekuatan Kiri mengalami peminggiran dan penyangkalan total: istilah kelas disingkirkan dari diksi politik dan ilmu sosial di Indonesia.
Dengan demikian, membayangkan bahwa Islam dan Kiri pernah memiliki sejarah kolektif yang heroik dan berarti dalam panggung dunia sering dianggap sebagai ilusi atau bahkan kesesatan intelektual. Padahal, sebagaimana Ridha buktikan, relasi itu memiliki jejak historis dan material yang nyata.
Istilah, Posisi Analitis, dan Persenyawaan Islam–Kiri
Istilah Kiri sendiri sejatinya sarat muatan sejarah dan ideologis yang lahir dari pengalaman Barat. Saya sendiri lebih memilih istilah progresif, tapi karena ‘Kiri’ sudah menjadi diksi yang mewakili posisi analisis dan keberpihakan terhadap praksis ekonomi politik kontemporer, maka kita bisa memakainya, sebagaimana Kiri Islam dipakai Hasan Hanafi. Persenyawaan atau konvergensi Islam dengan Kiri tidak berarti Islam sebagai agama diposisikan setara dengan pemikiran buatan manusia. Kiri adalah posisi analitis, bukan posisi keimanan atau tauhid. Islam di sini adalah ekspresi keberislaman kita sebagai umat Muslim dengan segala realita sosialnya. Karena kolonialisme dan kapitalisme telah menghasilkan eksploitasi dan penjajahan modern di muka bumi, maka kita perlu pisau analisis yang cukup tajam, yaitu secara teoretis kuat dan dalam, tapi tak berhenti pada renungan filsafat, diskursus dan akrobat hermeneutik, melainkan menjadi panduan bagi strategi dan horizon perlawanan dan membayangkan rekonstruksi dunia yang lebih baik. Di sini, Islam dan Kiri bersenyawa karena teori, visi, dan praktik bertemu – meski dengan segala gesekannya.
Di titik ini, Islam dan Kiri bertemu: teori, visi, pragmatisme, dan perlawanan bertaut, meski tetap dihuni oleh ketegangan internal.
Posisi Ridha dalam Lanskap Studi Islam–Kiri
Memang, banyak cendekiawan yang telah menelusuri relasi Islam dan Kiri. Para cendekia ini menelaah sumber sejarah, membangun tradisi epistemik antara iman dan kritik sosial, serta merumuskan cara berpikir yang menautkan gagasan Islam dan pembebasan. Salah satu yang terbaru adalah Hongxuan Lin dalam Ummah Yet Proletariat (2023) yang menggali interaksi ini dalam konteks Indonesia secara mendalam di era perjuangan menuju kemerdekaan.
Karya Muhammad Ridha mengambil pendekatan berbeda: ia tidak menulis monografi atau historiografi yang ambisius, melainkan menyajikan kompilasi karya sebagai pengantar konseptual yang mendasar, relevan, dan sangat dibutuhkan di era masa kini di mana ruang-ruang pemahaman sejarah Indonesia telah terbuka untuk ditinjau ulang. Dia memulai dari kegelisahan kontemporer—kritik terhadap buku Ahmet T. Kuru, Otoritarianisme dan Ketertinggalan Dunia Muslim. Pertanyaan sederhana namun mengguncang yang ia ajukan adalah: mengapa publik dan para cendekiawan Muslim begitu reseptif terhadap kritik liberal atas kemunduran Dunia Islam sebagaimana diungkapkan oleh Kuru? Mengapa seolah tidak ada alternatif lain atau sudut pandang berbeda terhadap sejarah Dunia Islam?
Pertanyaan ini membuka ranah diskusi tentang fungsi epistemik masyarakat Muslim hari ini: kecenderungan pasif menerima kritik liberal yang meletakkan kemunduran pada kelemahan internal Islam sendiri, tanpa memperhitungkan struktur kolonialisme dan kapitalisme global yang melingkupinya.
Begitu senyapnya penerimaan kita terhadap karya-karya bermutu, mendalam dan kaya riset yang dilakukan tentang sejarah kontribusi Kiri dalam Dunia Islam – seolah terkubur oleh meriahnya pendanaan proyek-proyek pengetahuan yang berkiblat pada ideologi liberal-sekuler. Tempat di mana para komentator dan cendekiawan publik diberi panggung untuk menyebarkan gagasan liberal mereka lewat proyek penerjemahan, beasiswa ke luar negeri untuk kepentingan neo-imperialisme, dan lembaga-lembaga beramai-ramai mengabaikan kayanya tradisi pemikiran Kiri. Yang terjadi kemudian adalah pelanggengan demonisasi dan bentuk karikatur dari tradisi Kiri sebagai ‘sebatas’ ideologi, paham sektarian, non-demokratis, ateis, deterministik dan seterusnya.
Narasi Historis: Kolonialisme, Komunisme, Nasionalisme
Ridha menunjukkan bahwa akar utama kemunduran Dunia Islam adalah kolonialisme—bukan akibat dominasi ulama atau militer sebagaimana diklaim oleh Kuru. Ia menjelaskan bagaimana kolonialisme berevolusi menjadi kekuatan liberalisme global yang memaksa negara-negara Muslim untuk tunduk ke dalam kerangka ekonomi kapitalis.
Oleh karena itu, buku ini adalah kompilasi tulisan yang disusun berdasarkan lintasan dialektik antara Islam dengan kolonialisme, kapitalisme, komunisme, dan nasionalisme. Setiap bab dirancang untuk menunjukkan bagaimana Islam merespons dan dibentuk oleh tekanan dari kekuatan eksternal dan internal ini.
Bagian penutup buku, “Palestina Milik Kita: Warisan Berdarah Imperialisme di Dunia Islam”, menjadi inti reflektif sekaligus pengait sejarah umat Islam global hingga hari ini. Dari An-Nakbah 1948 hingga era kita sekarang di tahun 2025 dan kita sendiri menyaksikan live streaming dalam skala yang lebih masif, genosida di Gaza. Palestina masih berdarah. Namun, berbeda dengan semangat perlawanan Dunia Islam di tahun 1940an hingga 1970an lewat sanksi ekonomi, embargo minyak, dan sokongan terhadap gerakan bersenjata, kali ini kita saksikan betapa kayanya negara-negara mayoritas Islam, tapi rezim-rezim penguasa era ini tak tampak gairah perlawanan tak lagi menggema selain retorika dan kecaman verbal – yang mungkin lebih rendah dari selemah-lemah iman. Pelayaran Freedom Flotilla lebih punya nyali.
Muhammad Ridha mengingatkan kita bahwa perlawanan terhadap neo-imperialisme bukan angan-angan. Perlawanan ini pernah menjadi nyawa kaum Muslim di masa lalu. Kegagalan Dunia Islam saat ini merespon genosida Gaza bukan lagi bentuk kemunduran Dunia Islam yang memang sudah mundur, tapi sekarang ini yang kita hadapi adalah ‘kehampaan’ Dunia Islam. Jika dahulu umat Islam membalas penjajahan dengan solidaritas negara-negara Muslim, kini kita menyaksikan negara Muslim justru enggan menghadapi konsekuensi geopolitik. Retorika dan kecaman verbal tampak semakin lemah dibanding perlawanan nyata. Keadaan ini bukan sekadar kemunduran, tetapi gejala kehampaan: “the hollowing of the Islamic world.” Dalam indikator modern, sebagian negara mayoritas Muslim mungkin mengalami pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang pesat, sementara sebagian lainnya tersaruk oleh kemelut pertarungan rezim, gejolak protes massa, hingga peperangan. Ini bukan lagi kemunduran, tapi Islam sebagai bangunan utuh yang mengatur dimensi material dan spiritual umat seperti berongga di dalam. Masjid-masjid megah tetap bertumbuh, tapi problem kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi masih menjangkiti kekuasaan.
Ketika penguasa telah bersekutu dengan kekuatan kapital-imperialis, harapan legitimasinya hanya bisa bergantung pada umat dan ulama yang masih berpihak pada kaum tertindas dan kebenaran melawan ketidakadilan. Sejarah mencatat bahwa sinergi ini pernah nyata. Di Indonesia, misalnya, tahun 1888 di Banten, para ulama dan pemimpin tarekat sufi bersatu membangun front persatuan melawan penjajah. Demikian pula pemberontakan Banten 1926, yang memperlihatkan persenyawaan ulama, jawara, kaum komunis, dan rakyat melawan kolonialisme dan elite komprador. Keterpaduan ini bukan sekadar moral simbolik, tapi akar dari antagonisme kelas yang lahir akibat kolonialisme Belanda. Rakyat menjadi tenaga murah bagi pasar global dan kaum aristokrat lokal. Maka perlawanan yang dihadirkan bukan hanya spiritual, melainkan material—sebuah jihad kelas melawan sistem imperial.
Catatan Kritis
Dari pembacaan terhadap buku ini, ada sejumlah ruang yang saya rasa bisa diperluas atau diperdalam:
1. Redefinisi “Dunia Islam” dalam Konteks Kontemporer
Kita perlu mendudukkan kembali makna Dunia Islam. Pada masa kalifah klasik hingga awal abad ke-20, jaringan umat bersifat transnasional. Namun kini umat kehilangan pusat simbolik politiknya. Maka, pada konjuntur mana pengertian geopolitik dan horizon pemikiran kita soal Dunia Islam itu bergeser, dan seperti apa transformasinya? Jika di abad pertengahan sampai ke awal abad kedua puluh kita masih memiliki suatu entitas kekuatan regional maupun internasional bernama khalifah, tersebar titik-titik kekuasaan dan pertumbuhan pesatnya di berbagai tempat, maka sejak Dinasti Ottoman runtuh dan Palestina jatuh ke tangan penjajah dan Zionis, kita kehilangan simbol dan representasi.
Tahun-tahun 1950-1970an, umat Islam kemudian membentuk negara-bangsa modern, yang merupakan warisan dari pola penjajahan kolonialisme Eropa. Ada perlawanan untuk solidaritas terhadap ingatan dan sisa-sisa Dunia Islam. Ada revolusi, ada gerakan perlawanan bersenjata di berbagai wilayah mayoritas Muslim. Setelah senja itu datang, di era fajar neoliberalisme tahun 1980an, imaji soal ‘Dunia Islam’ seolah hanya menyisakan ‘umat Islam’ yang terbelah terutama berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, aliran, dan bangsa. Legitimasi umara dan ulama tak lagi dapat mengklaim otoritas tunggal seperti masa khilafah.
Kolonialisme telah meruntuhkan infrastruktur sosial, legal formal dan politik Islam. Syariah direduksi menjadi hukum normatif yang parsial; wacana soal khilafah kerap dikriminalisasi. Sebaliknya, ‘demokrasi’ yang dalam konsep dan praktiknya sebenarnya amat luas dan beragam, dijadikan sesuatu yang dianggap universal dan benar dengan sendirinya, seolah menjadi dogma tanpa refleksi ideologis dan tanpa kita mempertanyakan asumsi-asumsi dasarnya. Kapitalisme merasuk ke dalam kehidupan umat, menundukkan mereka sebagai kelas proletar global.
2. Menempatkan “Kebangkitan Islam dan Komunisme” dalam Proyek Pengetahuan
Tema persenyawaan Islam dan komunisme sepatutnya ditempatkan dalam momentum sejarah: periode ketika kolonialisme, kapitalisme, dan konflik dunia menciptakan ruang bagi solidaritas lintas perbatasan. Revolusi dan pergolakan muncul di Asia, Afrika, Timur Tengah. Gelombang feminis sosialis juga memperkaya wacana pembebasan.
John Sidel dalam bukunya Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia (2021) menggambarkan bagaimana ide-ide revolusi dan nasionalisme terpadu dalam ruang kosmopolit kolonial. Perjalanan haji menjadi ruang konsolidasi ide transnasional. Intelektual Muslim yang belajar ke Eropa menjalin relasi dengan gerakan pembebasan global. Solidaritas dengan Bolshevik bukan sekadar strategi politik pragmatis, melainkan manifestasi kebutuhan global membentuk front perlawanan terhadap imperialisme. Inilah masa ketika karya Marx dan Engels diterjemahkan dan mempengaruhi gerakan Muslim progresif di dunia kolonial.
Persenyawaan Islam dan komunisme tak bisa direduksi sebagai tindakan oportunistik. Ini adalah kerja pemikiran: usaha melakukan sintesis dari nilai keadilan Islam dengan kerangka materialisme historis. Itu kenapa penting untuk menambahkan bahwa keberhasilan persenyawaan Islam dan Komunisme, Sosialisme dan Marxisme tidak sebatas pada momentum insidentil dan rangkaian panjang dari semangat anti-imperialisme sebagai peluang atau langkah taktis saja. Persenyawaan tersebut bukan kecelakaan sejarah atau dimensi oportunistis dari kedua elemen. Tanpa teori dan ideologi, kekuatan perlawanan di mana pun tidak akan punya daya tahan, dan ekspansi sebagaimana yang kita saksikan dalam sejarah. Persenyewaaan ini bisa tumbuh juga karena ada proyek pengetahuan yang dibangun dan ikhtiar serius untuk mensintesiskan pemikiran dan nilai-nilai ajaran Islam dengan tradisi pemikiran Kiri. Mereka secara tajam mengkurasi, menseleksi, dan melakukan kerja-kerja intelektual – filsafat, politik, ekonomi – menjadi basis pemikiran mereka.
Tokoh-tokoh seperti Haji Misbach, Tan Malaka, Hasan Hanafi, dan Ali Syariati menunjukkan bahwa iman dan perjuangan kelas dapat dipersatukan dalam horizon pembebasan yang sama. Bahkan, Kongres Sarekat Islam 1917—bertepatan dengan Revolusi Rusia—menjadi tanda sinergi gagasan: Sarekat Islam Merah kala itu menyatakan kapitalisme sebagai sistem yang haram, dianggap sebagai bentuk penghisapan—argumentasi moral dan rasional yang menyatu.
3. Kedalaman Analisis atas Kapitalisme
Meskipun buku ini membahas kolonialisme, pembahasan tentang kapitalisme nyaris mendapat porsi sehingga ruang ini masih terbuka lebar untuk digali. Hal ini karena kolonialisme tak terlepas dari logika kapitalisme-kolonial. Syed Hussein Alatas, dalam The Myth of the Lazy Native (1977), menegaskan bahwa kolonialisme adalah ekspresi dari akumulasi modal melalui eksploitasi kekayaan kolonial.
Ridha memberi contoh eksploitasi India dan Gowa oleh kolonialisme Belanda. Di Gowa, Belanda membangun monopoli, melakukan kekerasan, dan membawa pembantaian—praktik yang sebelumnya jarang terjadi dalam struktur ekonomi lokal Nusantara. Juga sistem tanam paksa di Jawa (1830–1870) yang pernah menyumbang hingga 50% pendapatan negara Belanda, tanpa membangun kemajuan bagi rakyat Jawa, sebagaimana diungkap oleh Cornelis Fasseur dalam bukunya The Politics of Colonial Exploitation: Java, The Dutch and The Cultivation System (1994). Pendapatan Belanda ini adalah hasil langsung dari produksi gula dan kopi hasil tanam paksa para petani di Jawa yang dijual di pasar dunia saat itu. Sebagian dari keuntungan ini bahkan yang mendanai pembangunan kanal dan jalur kereta di Belanda.
Akibatnya, kelaparan, wabah penyakit dan kemiskinan meluas. Ben White dalam In The Shadow of Agriculture: economic diversification and agrarian change in Java, 1900-1990 (1991) mencatat bahkan di tahun 1905 sekitar 40% rakyat Jawa sudah tidak lagi memiliki tanah. Selanjutnya di era pascakolonial, Revolusi Hijau saat Orde Baru yang awalnya dianggap modernisasi pertanian justru memperdalam jurang kelas antara pemilik modal dan petani kecil. Gelombang selanjutnya muncul pada 1980-an lewat restrukturisasi struktural dan privatisasi, menjerat negara-negara Muslim dalam jerat utang dan ketergantungan eksternal. Umat Islam kini tersekat-sekat dalam perjuangan keseharian yang sangat material.
Eksploitasi ini memiliki basis material jelas: ekspansi kekuasaan untuk mengekstraksi nilai lebih dan surplus produksi dari wilayah jajahan demi kepentingan pusat. Logika kapitalisme adalah penggerak utama kolonialisme. Maka tak heran jika negara-negara Barat menjadi makmur sementara negeri jajahan terus termiskin. Melalui pendekatan ini, kapitalisme-kolonial menciptakan struktur penghisapan: memonopoli ilmu, teknologi, tenaga kerja, dan relasi produksi—untuk akumulasi modal di pusat kekuasaan.
Rekonsiliasi Sejarah dengan Materialitas Politik
Kini kita hidup di era kapitalisme matang, di mana negara-bangsa menjadi bentuk dominan peradaban modern dan kolonialisme berpindah wujud menjadi hegemoni ekonomi budaya. Namun sejarah mengajarkan bahwa di setiap dominasi selalu ada retakan—ruang bagi kepekaan, kesadaran, dan perlawanan. Membayangkan kebangkitan Dunia Islam kontemporer tidaklah mungkin tanpa memahami kapitalisme: mekanismenya, relasi sosialnya, serta kontradiksinya. Kita harus menautkan sejarah ke dalam analisis material agar narasi imajiner tidak kehilangan pijaknya. Ini pentingnya metode materialisme historis, artinya sejarah tak hanya berhenti pada deskripsi atau romantisme masa lampau; melainkan mesti menelisik relasi produksi, kondisi kerja, struktur kelas, dan transformasi ruang kehidupan umat sekarang. Hanya dengan demikian kita mampu menantang mitos kapitalisme yang dianggap ‘baik’ dan ‘Islami’, untuk kemudian memperkaya horizon dan arah perjuangan.
Buku Sejarah Kiri Dunia Islam hadir bukan sekadar sebagai refleksi teoretik, melainkan sebagai pintu menuju agenda intelektual-praksis baru. Ia menguatkan bahwa Islam dan Kiri—meski dalam ketegangan—masih memegang potensi untuk membayangkan dunia yang adil, egaliter, dan beriman. Semoga karya Muhammad Ridha ini menjadi bacaan di fakultas-fakultas sosial, ilmu politik, filsafat, sejarah dan studi Islam. Semoga generasi muda Muslim kembali menulis sejarahnya sendiri—dengan iman dan keberpihakan yang jelas, keberanian, dan analisis yang tajam.
Catatan: Penulis resensi ini menulis kata pengantar untuk buku Sejarah Kiri Dunia Islam. Namun, ulasan ini ditulis secara independen dan mencerminkan pembacaan kritis yang berjarak dari keterlibatan tersebut. Segala pandangan dan interpretasi yang disampaikan di sini sepenuhnya merupakan hasil refleksi penulis sebagai pembaca dan peneliti.
Profil buku:
Judul: Sejarah Kiri Dunia Islam
Penulis: Muhammad Ridha
Penerbit: Intrans Publishing
Jumlah halaman: 144 halaman
Tahun terbit: 2025

Berikhtiar untuk memproduksi, mewadahi dan mendakwahkan diskursus keislaman progresif sekaligus menekankan komitmennya untuk selalu berpihak pada umat yang terzalimi.