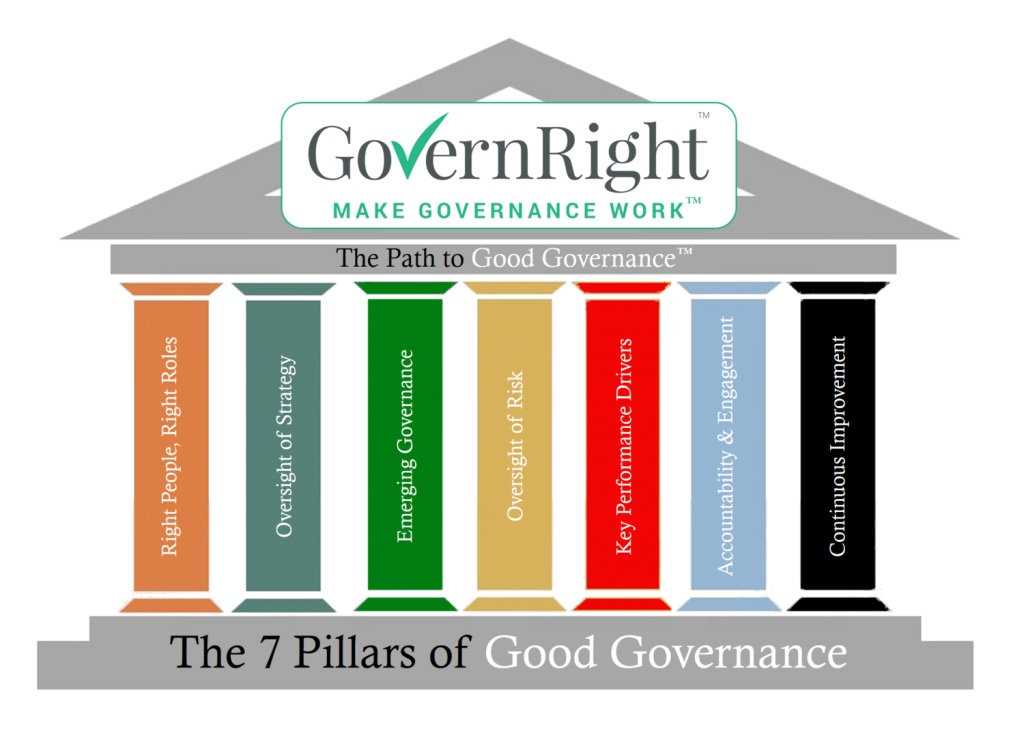

Tulisan ini diterjemahkan oleh Rizki Affiat dari bab ‘The Seductiveness of Good Governance’ oleh Rita Abrahamsen dalam ‘Is Good Governance Good for Development?’ oleh Jomo Kwame Sundram et al. (ed.). Bloomsbury Publishing PLC, 2012.
Pengantar editor:
Metodologi tulisan ini bersumber dari telaah atas dua dokumen Bank Dunia yang mengadvokasi wacana dan kebijakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Meski tulisan ini menggunakan contoh benua Afrika secara umum, keseluruhan dari isi artikel ini relevan dalam konteks global, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2006 lalu misalnya, Presiden Bank Dunia (saat itu) Paul Wolfowitz menyampaikan pidatonya bertajuk ‘Good Governance and Development – A Time for Action’ dalam kunjungan singkatnya ke Jakarta. Sembari bernostalgia tentang perasaannya mengunjungi Indonesia, yang disebutnya sebagai ‘pulang kampung’, Wolfowitz tak lupa menyapa dan memuji perjuangan rekan-rekan lamanya seperti Bambang Harymurti, Goenawan Muhamad, hingga CSIS. Seperti yang disebutkan oleh Rita Abrahamsen dalam artikel ini, yang terbit enam tahun setelah kunjungan Wolfowitz ke Indonesia, diskursus tata kelola pemerintahan yang baik masih konsisten dengan buzzwords-nya seperti pengembangan ‘sektor swasta’, ‘masyarakat sipil’, dan ‘akuntabilitas pemerintah’, termasuk di dalam Laporan 2018 Bank Dunia terbaru. Apa implikasinya bagi rakyat dari kata-kata ini, yang oleh sang penulis disebut sebagai ‘rayuan maut’?
Secara umum, kritik Rita Abrahamsen pada argumen diskursus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/TKPB (Good Governance)ada pada watak TKPB yang mengusung demokrasi kapitalisme dan liberalisasi ekonomi. Ini dapat dibagi ke dalam empat poin: pertama, penggabungan antara destatisasi (pengurangan peran negara) dan demokrasi; kedua, legitimasi baru untuk liberalisasi ekonomi dalam bentuk Structural Adjustment Programmes (SAP); ketiga, apapun asal bukan negara: SAP, kelompok borjuasi, budaya kapitalisme pribumi, hingga masyarakat sipil dianggap sebagai kekuatan pembebas melawan penindasan negara; dan keempat, demokrasi menjadi urusan domestik, tunduk pada tata dunia yang tidak demokratis. Artikel ini signifikan dalam melihat bagaimana institusi neoliberal mendesain dan mereproduksi pengetahuan serta kebijakan yang menggunakan istilah-istilah bermuatan moral (“baik”) namun sangat problematis dan kontradiktif. Penjabaran lebih lanjutnya ada pada tulisan berseri ini. Silakan membaca!
***
Diskusi yang berlaku umum tentang pembangunan (development) cenderung mengabaikan faktor kekuasaan dari diskursus serta perannya dalam konstruksi dan pemeliharaan hegemoni Barat di Dunia Ketiga. Artikel ini menunjukkan bagaimana diskursus pembangunan telah mengonstruksikan Dunia Ketiga sebagai terbelakang (underdeveloped) dan karenanya menormalisasi dan melegitimasi hak Utara (global North) untuk mengintervensi, mengontrol dan membangun Selatan (global South). Fokusnya ada pada agenda tata kelola pemerintahan yang baik/TKPB (good governance) itu sendiri. Diskursus TKPB adalah suatu versi mutakhir dari ‘impian pembangunan’, memberi hak bagi Utara untuk mengembangkan dan mendemokratisasi Selatan dalam imajinya. Artikel ini lantas menunjukkan dua hal: pertama, bagaimana pihak internasional selalu hadir dalam politik domestik dan kedua, bagaimana intervensi internasional dimainkan oleh representasi diskursus pembangunan dari Dunia Ketiga. Diskursus demokrasi muncul sebagai bagian penting untuk memahami pembangunan di Afrika.
Berdasarkan dokumen-dokumen Bank Dunia, artikel ini memaparkan analisis teoretis dan tekstual dari diskursus TKPB dan bertujuan untuk menyorot inkonsistensi, penyingkiran, dan caranya dalam membungkam [diskursus lain]. Artikel ini berargumen bahwa diskursus tersebut menarasikan pemerintahan yang mengaburkan perbedaan antara demokratisasi dan pemunduran peran negara dari ranah sosial dan ekonomi, sehingga memberi legitimasi baru bagi liberalisme ekonomi dalam bentuk program penyesuaian struktural atau structural adjustment programmes (SAP). Legitimasi ulang ini dicapai dengan memberi imaji suatu negara intervensionis yang asing (alien) versus kapitalisme Afrika ‘pribumi’, dan melalui ketergantungan pada konseptualisasi liberal atas kekuasaan, negara, dan masyarakat sipil. Efek kunci dari diskursus TKPB adalah konstruksi dari penyesuaian struktural beserta institusi dan negara yang mempromosikannya sebagai kekuatan demokrasi: pembebas masyarakat sipil dari negara penindas. Namun, analisis lebih dekat dari klaim agenda untuk ‘memberdayakan masyarakat biasa’ ini menunjukkan bahwa diskursus tersebut mempreteli maknanya dari politik radikal, dan justru mengubahnya menjadi sangat instrumental. Pemberdayaan dalam TKPB menjadi nyaris sekadar sinyal bahwa masyarakat harus mengambil beban mereka dan membuat proyek pembangunan lebih berbiaya efisien: sekali lagi, nyaris sebagai penggabungan demokrasi dan liberalisme ekonomi dalam diskursus TKPB menjadi jelas. Artikel ini juga menantang diskursus TKPB yang mengklaim memiliki sensitivitas budaya dan berargumen bahwa diskursus ini justru tidak berbeda secara siginifikan dari teori-teori modernisasi di masa lalu yang membentuk imaji masyarakat ideal yang dikonstruksikan oleh nilai-nilai dan pengalaman dunia Barat.
Kekuatan dari diskursus pembangunan, menurut Gilbert Rist, adalah pada kekuasaannya untuk merayu; ‘untuk mempesona, menyenangkan, memikat, mengusung mimpi, tapi juga menyalahgunakan, memalingkan dari kebenaran, mengelabui’ (Rist 1997:1). Janji untuk memberantas kemiskinan begitu membujuk sehingga meskipun sejarah pembangunan dilumuri oleh berbagai kegagalannya, kepercayaan terhadap pembangunan tetap bertahan. Berbagai kegagalannya telah menerbitkan teori-teori baru, masing-masing mengklaim telah menemukan solusi riil bagi problem pembangunan. Agenda TKPB merupakan bagian dari teori mutakhir dari rangkaian panjang ini.
Artikel ini tidak fokus pada implementasi dari rekomendasi kebijakan yang memenuhi agenda TKPB, maupun berupaya untuk mengoreksi atau memberi teori pembangunan yang ‘benar’. Melainkan, fokus pada diskursusnya sendiri, yang menarasikan pembangunan sebagai ketiadaan TKPB. Tujuannya adalah menunjukkan, tak hanya diskursus soal konseptualisasi demokrasi namun juga apa yang dibungkam dan disingkirkannya, dengan cara menggunakan rayuan kekuasaan untuk mengelabui. Hal ini akan memampukan kita untuk menunjukkan dampak dari ide-ide pembangunan ini pada proses sosial yang lebih luas, intervensi dan praktik apa saja yang absah bagi mereka, serta aksi dan kebijakan apa saja yang dibuat menjadi tidak absah dan dikecualikan.
Hampir setiap analisis dari watak ini beresiko untuk merepresentasikan diskursus pembangunan sebagai monolitik, tidak berubah dan tidak tertantang, dari konstruksi atas kesepakatan dimana ada keberagaman, perselisihan dan fleksibilitas. Memang ada suara-suara menentang di dalam pembangunan dan tidak ada suatu keseragaman dan kesepakatan utuh yang bisa dibilang ada antara berbagai negara-negara donor dan organisasi pemberi bantuan. Meski demikian, diskursus pembangunan hari ini justru lebih homogen ketimbang era sebelumnya. Apa yang disebut sebagai ‘Washington Consensus’ (Williamson 1993) masih diterima oleh mayoritas donor multilateral dan bilateral, dan ada kesepakatan umum pada hasrat untuk liberalisme ekonomi dan demokrasi liberal. Ketidaksepakatan dibuat menjadi isu kecil dan detil soal apa yang penting dalam ragam aspek dari TKPB dan ‘pembangunan’, sedangkan prinsip-prinsip menyeluruhnya tetap tidak tertantang. Oleh karenanya, pada tingkat yang amat dasar ini, absah bagi kita untuk bersuara soal keberadaan diskursus pembangunan yang dianut dan diadvokasi oleh para donor dan kreditur di Utara sebagai model yang perlu diikuti oleh Selatan.
Intervensi Negara yang Terasing, Kapitalisme Demokrasi yang Pribumi
Konsep TKPB pertama kali diperkenalkan dalam diskursus pembangunan oleh laporan Bank Dunia tahun 1989 bertajuk Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Dokumen ini merupakan pernyataan kuat oleh kepemimpinan intelektual dari institusi komunitas donor (Gibbon 1993), dan sejak saat itu, Bank Dunia telah memimpin ‘pemurnian’ artikulasi dan ideologis dari doktrin pembangunan baru. Laporan 1989 ini, bersama dengan studi Bank Dunia bertajuk Governance and Development (1992a), masih merepresentasikan pernyataan resmi yang tegas dan paling keras tehadap pemikiran pembangunan terkini, locus classicus dari literatur pembangunan.Analisis saya tentang diskursus pemerintahan berpusat pada dua dokumen ini, tapi juga dari artikel-artikel yang dipublikasikan oleh dua anggota senior staf Bank Dunia dan laporan rangkumannya berjudul Governance: The World Bank’s Experience (1994). Secara umum, donor bilateral sejalan dengan pandangan yang diungkapkan dalam dokumen-dokumen ini, dan meskipun diskursus pembangunan kontemporer tidak bisa dilihat secara monolitik dan tidak berubah, ada kesepakatan umum tentang elemen mendasar dari TKPB sebagaimana dikonstruksikan oleh Bank Dunia.
Konstruksi Bank Dunia tentang TKPB dimulai dari penolakan model pembangunan di masa lalu. ‘Upaya pembangunan pascakemerdekaan telah gagal’, begitulah dikatakannya pada kita, ‘karena strateginya disalahpahami’ (Bank Dunia 1989:3). Menurut Bank Dunia, saat ini ada ‘konsensus yang meningkat’ bahwa strategi-strategi ini ‘menekankan terlalu banyak harapan pada kecepatan industrialisasi yang ditopang negara’ dan secara keliru mendorong pemerintah di negara-negara Afrika untuk ‘tergesa-gesa menuju ‘modernisasi’, meniru, tapi tidak mengadopsi model Barat’ (Bank Dunia 1989:83, 3). Setelah kemerdekaan, pemerintahan negara-negara Afrika dicangkokkan ke masyarkat tradisional dan seringkali terasing dari budaya pribumi’ (Bank Dunia 1989: 38).
Penasehat kebijakan senior Bank Dunia juga membuat poin yang sama, menekankan bahwa ‘institusi-institusi negara yang didasari oleh prinsip-prinsip birokrasi Weberian…tidak sesuai dengan kepercayaan dan praktik masyarakat Afrika’ (Landell-Mills, 1992:543). Negara pascakolonial, singkatnya, adalah ‘contoh sempurna dari sistem terasing yang dipaksakan dari atas’, dan karena dasar pemikiran budaya yang mendasari institusi negara di Barat asing bagi benua tersebut, institusi-institusi ini ‘mulai runtuh begitu pemerintahan kolonial pergi’ (Landell-Mills 1992: 545, 543). Melihat ke belakang, ‘bencana ekonomi, politik dan sosial’ di Afrika bisa disalahkan pada ‘kelemahan mendasar dalam paradigma pembangunan yang berlaku’ (Landell-Mills 1992:543).
Pembelajaran telah diambil dan teori pembangunan telah diamandemen. Sementara upaya-upaya pembangunan yang dipimpin negara telah gagal karena mereka ‘tidak membangun dari kekuatan masyarakat tradisional’, agenda TKPB mengklaim berbeda (Bank Dunia 1989:60). Strategi pembangunan di masa lalu membuat pemisahan kuat antara yang modern dan tradisional, menyingkirkan yang tradisional dan membuatnya sangat jelas bahwa ‘masyarakat modern berarti “kemajuan”’ (Bank Dunia 1989:60). Agenda TKPB mengklaim telah memiliki derajat kesadaran budaya yang lebih tinggi dan sesuai, karena ada ‘keterhubungan dekat antara pemerintahan, relevansi budaya dan komponen masyarakat sipil’ (Landell-Mills 1992:567). Paradigma pembangunan baru mengakui, dalam kata-kata Bank Dunia, bahwa ‘jauh dari menghalangi pembangunan, banyak nilai dan institusi pribumi penduduk Afrika dapat mendukungnya’ (Bank Dunia 1989:60). Oleh karenanya, TKPB tidak mengadvokasi suatu ‘ketergesaan untuk modernisasi’, melainkan pemahaman atas kebutuhan untuk ‘secara progresif membentuk ulang institusi-institusinya agar lebih sejalan dengan tradisi, kepercayaan dan struktur dari komponen masyarakat’ (Landell-Mills 1992:545), dan bahwa ‘tiap negara harus merancang institusi-institusi yang cocok dengan nilai-nilai sosialnya’ (Bank Dunia 1989:60). Perubahan tidak dapat dipaksa dari luar oleh badan-badan pembangunan, dan akan lebih efektif hanya jika ia ‘berakar kuat dalam masyarakatnya’, dan program-program Bank Dunia harus ‘mencerminkan karakter nasional dan konsisten dengan nilai-nilai budaya negara tersebut’ (Bank Dunia 1992a: 12; 1989: 193).
Di permukaan, usulan-usulan ini sangat menggoda dan hampir seiring akal sehat. Hasrat untuk membangun masyarakat dari nilai-nilai mereka, ketimbang yang diimpor, tampaknya di masa kini didukung oleh baik politik kiri maupun kanan. Pengakuan atas watak ‘asing’ dari negara modern dan tidak berakarnya pada masyarakat pribumi juga tercermin dari perdebatan masa kini.
Namun, diskursus Bank Dunia menunjukkan dua fungsi penting dalam diskursus pemerintahan. Pertama, ia bertujuan untuk memisahkan agenda TKPB dan para pendukungnya dari kegagalan pembangunan di masa lalu. Strategi pembangunan di masa lalu bisa saja akibat gagal paham, namun kesalahan-kesalahan ini sekarang telah dikoreksi oleh para donor, yang telah menemukan solusi ‘riil’ bagi problem di Afrika. Dengan cara ini, aparatus pembangunan dan Bank Dunia secara khusus tetap tidak ternodai oleh kesalahan-kesalahan sebelumnya dan masih mempertahankan hak moral untuk melanjutkan upaya pembangunan.
Kedua, representasi tidak hanya bertujuan untuk mengkonstruksikan suatu imaji negara Weberian modern sebagai hal yang asing bagi Afrika tapi juga mendelegitimasi pembangunan yang dipimpin negara.Negara dikonstruksikan sebagai temuan Barat, hasil dari ideologi pihak asing dan teori pembangunan yang salah arah, dipaksa dari atas untuk memodernisasi masyarakat pribumi. Karena negara adalah suatu bentuk paksaan asing, semua yang dilakukan negara menjadi tercela. Intervensi negara, entah itu layanan bagi kesejahteraan masyarakat ataupun kepemilikan usaha, ditakdirkan untuk gagal karena tidak sejalan dengan nilai dan adat istiadat lokal. Dalam representasi ini, pembangunanisme yang berlaku atau turut-campur negara (state interventionist) menjadi musuh rakyat, penyebab dari keterbelakangan dan penderitaan Afrka. Agenda TKPB, sebaliknya, muncul sebagai pembebas yang akan memberi ruang bagi tak hanya pembangunan melainkan juga pembebasan bagi nilai-nilai pribumi yang sejati dalam masyarakat. Pada titik ini, diskursus TKPB melakukan ‘pelintiran’ yang licik. Di saat negara dan kapitalisme negara dianggap sebagai artefak impor, kapitalisme direpresentasikan sebagai suatu bagian integral dari budaya pribumi Afrika, secara sempurna sesuai dengan nilai-nilai lokal dan tradisional.
Diskursus pemerintahan menggambarkan masyarakat Afrika memiliki energi kapitalis dan jiwa kewirausahaan yang membuncah namun tertekan. Di bawah judul utama ‘tradisi pasar Afrika’, Bank Dunia mengingatkan kita bahwa ‘kewirausahaan memiliki sejarah panjang dalam sub-Sahara Afrika. Bagian dari perdagangan jarak jauh dengan rute karavan yang telah berjalan jauh ke belakang sejak abad kesebelas di benua tersebut’ (Bank Dunia 1989: 136). Kita diminta lebih jauh untuk mengingat bahwa aktivitas pertambangan Zimbabwe yang jaya memiliki hubungannya dengan perdagangan di Arab dan pusat ekspor di pesisir tenggara, dimana sistem pertukaran yang liberal beroperasi dan toleransi berlaku. Di Afrika masa kini, sebaliknya, pembangunan yang dipimpin negara telah menahan laju aktivitas sektor swasta. Dalam ‘ketergesaan menuju modernisasi’ yang salah arah ini, pemerintah ‘sangat meremehkan kekuatan dan potensi kewirausahaan penduduk Afrika’ (Bank Dunia 1989: 136). Sumber daya yang akan besar diarahkan untuk usaha publik, dan kebijakan ini ‘telah menggeser para wirausaha ke sektor informal’ dan ‘firma lokal yang berjejalan tidak mendapat akses ke pasar dan sumber daya finansial’ (Bank Dunia 1989: 136-7). Namun, ‘terlepas dari permusuhan dari pemerintah pusat’, para wirausaha lokal telah menunjukkan vitalitas yang hebat’, dan Bank Dunia berargumen bahwa berbeda tajam dengan kegagalan usaha publik, ‘sektor informal di hampir semua tempat telah menunjukkan sukses yang luar biasa’ (Bank Dunia 1989: 59,38).
Tak hanya kapitalisme di Afrika yang mampu mengatasi segala rintangan, tapi ia telah berhasil melakukannya secara konsisten dengan budaya asli Afrika. Menurut Bank Dunia, kewirausahaan dalam ‘sektor informal dikelola dan didukung oleh nilai dan tradisi lokal’ (Bank Dunia 1989: 140). Para pedagang dan pengrajin menjalankan aktivitas mereka ‘sesuai dengan adat istiadat dan aturan yang telah lama berlaku dan diatur melalui institusi-institusi di akar rumput (Bank DUnia 1989: 136). Oleh karena itu, diskursus TKPB berbicara tentang pembiayaan sektor informal dalam bentuk kelompok menabung, perputaran pendanaan dan pengaturan informal lainnya dimana ‘kesetiaan antarpersonal’ lebih penting ketimbang jaminan formal dan keuntungan (Bank Dunia 1989: 140-1). Klaim ini tidak menyebut soal para lintah darat yang menghisap bunga pinjaman dengan biaya tinggi. Alih-alih, kapitalisme sektor informal diberikan wajah penuh kasih sayang dan kepedulian, tidak terlalu peduli dengan keuntungan karena kebergantungannya pada ‘hubungan personal’ (Bank Dunia 1989: 140).
Dengan cara ini, diskursus TKPB mengkonstruksikan oposisi biner antara intervensi negara yang dianggap asing, yang diasosiasikan dengan kegagalan pembangunan di masa lalu, dan kapitalisme pribumi, yang merepresentasikan dasar bagi keberhasilan pembangunan di masa depan. Sementara tidak ada bantahan soal performa negara-negara Afrika yang suram, konsekuensi jelas dari oposisi biner ini adalah ketertundukkannya pada legitimasi dari penyusutan negara dan layanannya, sejalan dengan program penyesuaian struktural (SAP). Karena negara dianggap penindas yang asing, pembatasan aktivitas negara seolah menjadi ramah-rakyat, suatu usaha demokratis, hampir pada taraf dimana pengurangan peran negara (destatisation) dibuat menjadi sinonim dengan demokratisasi. Penggabungan dari penyusutan-negara dengan demokratisasi ini merupakan watak esensial dari diskursus TKPB, dan, sebagaimana akan kita lihat, bergema dalam beragam samarannya di keseluruhan diskursus.
Penggabungan penyusutan-negara dan demokratisasi memiliki akarnya pada persepsi demokrasi dan liberalisme ekonomi sebagai dua sisi dari satu koin. Gagasan pembangunan kontemporer memandang demokrasi dan liberalisasi ekonomi sebagai proses yang saling terhubung dan menguatkan satu sama lain. Argumen ini bisa disentesiskan sebagai berikut: liberalisasi ekonomi diharapkan akan mendesentralisasi proses pembuatan keputusan dari negara dan menjamakkan pusat-pusat kekuasaan. Dampaknya diasumsikan akan mengarah ke pembangunan masyarakat sipil yang mampu membatasi kekuasaan negara dan menyediakan dasar bagi politik demokrasi liberal.
Namun, hak-hak demokrasi dilihat sebagai bentuk mengawal hak kepemilikan, yang berdampak pada terciptanya keamanan dan insentif yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Liberalisasi ekonomi dan demokrasi ini dianggap sebagai sinergi yang positif, dan Bank Dunia berargumen bahwa ‘legitimasi politik’ adalah ‘prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan’ dan pertumbuhan, dan bahwa reformasi ekonomi akan ‘sia-sia jika konteks politik tidak sesuai’ (Bank Dunia 1989: 60, 192). Banyak organisasi pembangunan dan donor bilateral sudah ikut latah dengan pandangan ini.
Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Douglas Hurd, misalnya, bersikukuh bahwa ‘TKPB berjalan seiring dengan kesuksesan pembangunan ekonomi. Dalam jangka pendek suatu pemerintahan yang otoriter atau korup mungkin bisa meraih kemajuan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, pemerintahan macam itu terbukti tidak efisien, dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sosial seefektif pemerintahan yang akuntabel’ (Hurd 1990: 4-5). Pandangan yang sama juga disampaikan oleh kebijakan pemerintah dari Partai Buruh, dengan mantan Menteri Luar Negeri Robin Cook menyatakan bahwa ‘dua dekade terakhir telah menunjukkan bahwa kebebasan politik dan pembangunan ekonomi saling menguatkan satu sama lain’ (Cook 1998).
Dalam diskursus TKPB, demokrasi muncul sebagai kerangka politik yang dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan ekonomi, dan dalam diskursus itu, demokrasi dan liberalisme ekonomi terhubung secara konseptual: tata kelola pemerintahan yang buruk setara dengan intervensi negara, dan TKPB setara dengan demokrasi dan liberalisme ekonomi. Dengan kata lain dari para dua pejabat senior Bank Dunia, tata kelola pemerintahan berarti pemerintah yang kompeten dan akuntabel yang ‘berdedikasi pada kebijakan ekonomi liberal’ (Landell-Mills dan Serageldin 1991: 307). Karena demokrasi dan liberalisme ekonomi secara konseptual terhubung dalam satu konsep ‘tata kelola pemerintahan’, kemungkinan untuk memahami potensi kontradiksi antara keduanya menjadi mustahil di dalam parameter diskursus. Untuk berpihak pada demokrasi maka secara simultan juga berpihak pada ekonomi pasar bebas dan penyesuaian struktural. Fakta bahwa keduanya kadang berkonflik, sehingga misalnya, ketidakmerataan ekonomi yang dimunculkan oleh kompetisi kapitalis dapat mengurangi kesetaraan politik dan fungsi demokrasi, dianggap tidak bisa diterima oleh gabungan dari konsep tersebut. Ini juga turunan dari definisi di atas tentang tata kelola pemerintahan bahwa demokrasi akan mengarah pada TKPB hanya jika pemilihan umum memilih pemerintahan yang patuh pada ideologi pasar bebas. Ini tentu saja merupakan ketentuan yang tidak demokratis secara inheren, karena berupaya untuk mengekang cakupan pilihan politik. Dampaknya, secara singkat, adalah suatu determinasi a priori pada model ekonomi dan degradasi yang membuat pilihan konstituen menjadi prioritas kedua. Kemungkinan bahwa sebagian besar dari pemilihan umum di negara-negara miskin mungkin memilih solusi ekonomi dan politik yang berkonflik dengan visi agenda TKPB diabaikan dan dibungkam oleh diskursus ini.
Sebaliknya, agenda TKPB mengklaim untuk berbicara atas nama ‘rakyat jelata’ di Afrika, dan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk ‘memberdayakan’ mereka dan memampukan mereka untuk melawan negara yang asing dan penindas (Bank Dunia 1989: 54). Dengan cara ini, kesatuan tujuan yang esensial dikonstruksikan antara aparatus pembangunan dan ‘rakyat jelata’, bahwa mereka semua seolah menentang negara dan berupaya untuk menyusutkan perannya. Strategi agenda TKPB mendukung rakyat melawan negara adalah dengan cara memperkuat masyarakat sipil, suatu strategi yang secara intim terikat dengan liberalisme ekonomi.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berikhtiar untuk memproduksi, mewadahi dan mendakwahkan diskursus keislaman progresif sekaligus menekankan komitmennya untuk selalu berpihak pada umat yang terzalimi.
Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan di salah satu kampus kecil di Mojokerto Jawa Timur, saya sungguh tertarik dengan bahasan artikel ini mengingat hal-hal kritis semacam ini benar-benar jarang dibahas selama perkuliahan. Saya juga sering melihat antusiasme para dosen yang benar-benar terpikat dan selalu menggembar-gemborkan yang namanya Good Governance, Peningkatan SDM, serta Pemberdayaan Masyarakat seolah-olah itulah solusi atas semua masalah ini. Tetapi, mereka tak pernah sama sekali mencoba membahas tentang Kebijakan Neoliberalisme yang dibuat oleh Pemerintah. Terima kasih banyak sudah menulis seri artikel yang bermanfaat ini bagi saya
Sama-sama Bung. Semoga kita semua istiqamah dalam berjuang. Salam.